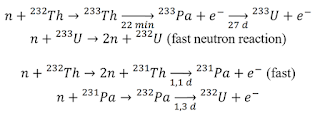Oleh: R. Andika Putra
Dwijayanto, S.T. (Peneliti Teknologi Keselamatan Reaktor)`
Terdeteksinya paparan
radiasi di atas dosis normal di Perumahan Batan Indah, Setu, Tangerang Selatan,
beberapa waktu yang lalu, memancing histeria konyol di berbagai lapisan
masyarakat. Sebagian memang karena tidak paham tentang aspek-aspek kenukliran
termasuk radiasi, dan yang seperti ini patut dimaklumi dan diberi pemahaman.
Namun, masalah lebih besar adalah dari kalangan anti-nuklir. Khususnya LSM
lingkungan eco-fascist seperti Greenpeace.
Sebagai LSM eco-fascist
yang terkenal akan sifat pseudosaintifiknya di seluruh dunia, Greenpeace tidak
ketinggalan pasti akan turut mengomentari penemuan radioaktivitas asing di
Perumahan Batan Indah. Benar saja, postingan Instagram Greenpeace Indonesia
memuat tulisan yang ujung-ujungnya mengkriminalisasi limbah nuklir dan menolak
PLTN [1]. Tidak ada yang baru dari “argumentasi” mereka, hanya
halusinasi-halusinasi usang yang diulang-ulang seperti radio rusak. Namun,
halusinasi Greenpeace harus dihentikan, kalau tidak mau masyarakat terus
dibodoh-bodohi oleh LSM eco-fascist pseudosaintifik ini.
Berikut adalah
“argumentasi,” kalau bukan halusinasi, Greenpeace dan kritikan terhadapnya.
//Ditemukannya radiasi
nuklir oleh Bapeten di sebuah tanah kosong di dalam kawasan Perumahan Batan
Indah, Serpong, Tangerang Selatan, dan serpihan radioaktif dengan kandungan
Caesium 137 atau Cs-137, membuktikan bahwa penanganan limbah radioaktif di
Indonesia dilakukan secara serampangan, tidak dilakukan dengan semestinya
sesuai aturan yang ada, dan sangat membahayakan masyarakat//
Pengelolaan limbah
radioaktif di Indonesia semua dilakukan oleh Pusat Teknologi Limbah Radioaktif
(PTLR) BATAN. Semua instansi yang menggunakan sumber radioaktif, entah BATAN
sendiri, Bapeten, PT Inuki, hingga berbagai industri dan rumah sakit, ketika
sudah selesai menggunakannya, semua wajib dilimbahkan ke PTLR. Praktik ini
telah berlangsung puluhan tahun dengan sebagaimana mestinya. Mayoritas, kalau
bukan semua, dilaksanakan sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang
berlaku [2].
UU No. 10 Tahun 1997
Tentang Ketenaganukliran, Pasal 23 Ayat 1 menyebutkan, “Pengelolaan limbah
radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan
Pelaksana.” [2] Siapa Badan Pelaksana yang dimaksud dalam UU ini? BATAN,
melalui salah satu pusatnya yakni PTLR. Pengelolaan limbah radioaktif telah
diatur melalui UU, yang merupakan ketetapan hukum tertinggi ketiga dalam
konstitusi Indonesia.
Masih di UU yang sama,
Pasal 24 ayat (1) mengatakan, “Penghasil limbah radioaktif tingkat rendah dan
tingkat sedang wajib mengumpulkan, mengelompokan; atau mengolah dan menyimpan
sementara limbah tersebut sebelum diserahkan kepada Badan Pelaksana,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.” [2] Artinya, yang berkewajiban
menyerahkan adalah penghasil limbah. BATAN hanya bertugas menerima dan
mengelola.
Dasar hukum pengelolaan
limbah radioaktif sudah jelas. BATAN telah melakukan tugasnya dengan konsekuen.
Tidak ada industri yang pengawasannya lebih ketat daripada industri nuklir;
terdapat pengawas pada tingkat nasional (Bapeten) maupun internasional (IAEA).
Kemungkinan penyelewengan dalam proses pengelolaan limbah radioaktif, dengan
demikian, diminimalisir sampai pada taraf nyaris tidak ada.
Maka, jika ada satu
kejadian ditemukannya material radioaktif yang tidak berada di tempat yang
seharusnya, lalu kemudian dikatakan pengelolaannya sebagai serampangan, tidak
semestinya, tidak sesuai aturan, dan sangat membahayakan masyarakat, pernyataan
seperti itu tidak kurang dari penyesatan publik, kebohongan yang nyata, dan
kebodohan yang tidak terperi.
Jelas saja bahwa
kejadian di Batan Indah merupakan sebuah keteledoran. Namun, jika kejadian itu
dijadikan justifikasi untuk mengatakan bahwa pengelolaan limbah radioaktif di
Indonesia dilaksanakan secara serampangan dan tidak sesuai aturan, sembari
mengabaikan sekian banyak limbah lain yang dikelola dengan baik oleh PTLR, maka
sesungguhnya Greenpeace sedang berhalusinasi. Sebuah halusinasi yang culas,
jahat, menyesatkan, dan berlawanan dengan amanat UUD untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa.
//Harus dilakukan
investigasi menyeluruh bagaimana limbah radioaktif tersebut bisa sampai di
tengah-tengah perumahan padat penduduk. Selain harus diteliti sejauh apa
cemaran radiasi tersebut pada tanah dan tanaman yang ada di lokasi, Cs-137
bersifat mudah teroksidasi dan larut dalam air. Juga apabila Cs-137 berbentuk
serbuk, ia akan juga dengan mudah terhirup oleh masyarakat//
BATAN telah melakukan
dekontaminasi terhadap petak tanah berukuran 10×10 m (100 m2) di samping
lapangan voli depan Blok J. Lokasi tersebut adalah lokasi yang tidak ditinggali
manusia, bahkan aktivitas manusia pun tidak. Per 18 Februari 2020, tingkat
radioaktivitas tanah terkontaminasi telah turun hingga 90%, menjadi 7 µSv/jam
[3]. Padahal, per 15 Februari 2020, paparan radiasi masih sebesar 98,9 µSv/jam
[4]. Artinya, sebagian besar kontaminan sudah berhasil dikeruk pada petak tanah
yang kecil tersebut. Apa implikasinya? Kawasan yang terkontaminasi sangat
sempit. Bahan kontaminan tidak bermigrasi terlalu jauh.
Cs-137 memang bersifat volatil,
mudah mencair dan menguap. Namun, mengingat sempitnya daerah terkontaminasi di
Batan Indah, bisa dipastikan bahwa migrasi sumber radioaktif tidak jauh.
Apalagi tidak terdeteksi adanya radioaktivitas tambahan di sumber air penduduk
sekitar [5]. Fakta yang entah kenapa diabaikan oleh Greenpeace.
Jika migrasi bahan
tidak jauh, kemungkinan terserap oleh vegetasi di sekitarnya juga rendah.
Lagipula, tidak ada juga yang mengonsumsi vegetasi di sekitar petak
terkontaminasi. Hal tersebut tidak sulit dipahami jika paham yang namanya risk
assessment. Namun, Greenpeace sepertinya tidak peduli soal risk assessment.
Mereka hanya peduli bagaimana memberi image buruk pada nuklir.
Cs-137 tidak dijual
dalam bentuk serbuk. Biasanya dalam bentuk encapsulated bahkan
double-encapsulated. Tidak ada relevansinya dengan kasus penemuan di Batan
Indah. Entah apa maksudya Greenpeace mengangkat hal ini, kalau bukan dengan
tujuan menakut-nakuti publik akan bahaya yang tidak ada.
//Saat ini tidak ada
solusi yang kredibel untuk pembuangan limbah nuklir jangka panjang yang aman.
Amerika selama ini menempatkan pembuangan limbah nuklirnya di Carlsbad, New
Mexico dengan kedalaman 655 m dibawah permukaan, dan mengajukan Yucca Mountain
sebagai tempat penyimpanan berikutnya tetapi mendapatkan begitu banyak
tentangan. Tidak hanya reaktor nuklir yang harus benar-benar aman dari
kesalahan teknis dan manusia, juga bencana alam; tetapi penyimpanan limbah
nuklir juga selalu meninggalkan jejak ketakutan tersendiri//
Para nuclear engineer sudah
tahu bagaimana membuang limbah radioaktif dengan selamat. Mereka tahu bagaimana
membuat kontainer limbah yang memadai dan lokasi repositori yang cukup baik.
Limbah radioaktif dari PLTN, jika ini yang dimaksud, dikonversi menjadi gelas
borosilikat yang kemudian dimasukkan dalam kontainer yang terdiri dari
berlapis-lapis bahan, mulai dari logam hingga beton. Kemudian, limbah ini
disimpan dalam repositori abadi [6].
Setidaknya ada tujuh
lapis pertahanan pada repositori abadi limbah PLTN, sebagaimana dijelaskan oleh
Prof. Bernard L. Cohen [7]. Pertama, ketiadaan air pada lokasi repositori
limbah, sehingga korosi bisa dicegah. Kedua, batuan yang tidak larut oleh air.
Ketiga, material penyegel tambahan berupa tanah liat, yang telah terbukti
mencegah migrasi produk fisi. Keempat, material casing kontainer limbah yang
tahan korosi.
Kelima, limbah
radioaktif dalam bentuk gelas borosilikat tidak larut oleh air. Keenam, migrasi
air tanah dalam menuju permukaan tanah membutuhkan waktu yang sangat lama.
Ketujuh, filtrasi dari bebatuan untuk memerangkap limbah yang somehow lolos
dari level-level berikutnya.
Cohen juga
mengungkapkan rendahnya probabilitas kebocoran kontainer limbah radioaktif
dalam menyebabkan korban jiwa. Disebutkan bahwa kematian yang mungkin diakibatkan
oleh kebocoran limbah radioaktif adalah 0,0014 kematian dalam 13 juta tahun
pertama setelah pembuangan limbah dan 0,0018 kematian dalam jangka waktu tak
terhingga [7]. Ini adalah bahasa statistik. Dalam bahasa awam, secara praktis
repositori abadi limbah radioaktif tidak dapat menyebabkan kematian akibat
kebocoran limbah.
Reaktor nuklir alam di
Oklo, secara praktis menjadi bukti sahih efektivitas pengungkungan limbah
radioaktif. Sekitar dua milyar tahun lalu, ketika kadar isotop fisil U-235 masih
berkisar 3% (saat ini 0,7% karena peluruhan alami), terbentuk reaktor nuklir
alami di daerah yang saat ini merupakan bagian dari negara Gabon, Afrika.
Kandungan uranium di Oklo ditemukan lebih rendah daripada yang seharusnya,
serta ditemukan adanya produk fisi serta elemen transuranik di dekatnya.
Penelitian menunjukkan
bahwa sebagian besar produk fisi penting dan seluruh elemen transuranik tidak
bermigrasi terlalu jauh dari lokasi reaksi fisi terjadi [8,9]. Hal ini luar
biasa mengesankan, karena selama dua milyar tahun, pergeseran produk fisi dan
transuranik tidak signifikan. Dengan teknologi kontainer abad 21, pengungkungan
limbah radioaktif secara praktis lebih kuat dan tidak menjadi persoalan.
Khususnya ketika produk fisi sudah lenyap dalam 300 tahun dan elemen
transuranik yang tersisa tidak bisa larut oleh air.
Ini belum termasuk
insinerasi elemen transuranik di reaktor maju, entah reaktor thorium maupun
reaktor cepat. Kedua jenis reaktor tersebut dapat ‘menghabisi’ transuranik
penyumbang radiotoksisitas limbah radioaktif sembari menghasilkan energi yang
bersih, murah, selamat, andal, dan berkelanjutan [10-15].
Pengelolaan ini jauh
lebih baik daripada, katakanlah, pengelolaan limbah panel surya dan turbin
angin. Limbah panel surya 300x lebih beracun daripada limbah radioaktif karena
kontaminasi kadmium, antimoni, dan timbal [16]. Panel surya sulit didaur ulang,
dan diperkirakan pada tahun 2050, jumlah limbah panel surya dapat mencapai 78
juta ton [17]. Tanpa ada rencana jelas bagaimana mendaur ulangnya.
Pengelolaan limbah
turbin angin tidak lebih mudah, mengingat bahan fiberglass yang digunakan
sebagai bahan kincir angin tidak bisa didaur ulang dan akan menimbulkan masalah
di masa depan [18]. Diperkirakan bahwa pada tahun 2050, limbah bilah turbin
angin akan mencapai 43 juta ton [19]. Lagi-lagi tanpa ada solusi bagaimana
menanganinya, selain ditumpuk begitu saja sembari mengotori lingkungan.
Dibandingkan limbah
panel surya dan turbin angin, yang notabene merupakan dua moda pembangkit yang
begitu dipuja-puja Greenpeace, pengelolaan limbah nuklir jauh lebih canggih,
terstruktur, memiliki rencana yang jelas, dan sebagian langkah telah
dilaksanakan dengan sukses.
Masalah pengelolaan
limbah radioaktif tidak pernah menjadi masalah teknis. Semua masalah yang ada
merupakan masalah politis, yang mana sebagian disumbangkan oleh LSM eco-fascist
seperti Greenpeace.
//Nuklir bukanlah
pilihan energi masa depan Indonesia. PLTN adalah investasi berbahaya dan juga
sangat mahal. Mengacu pada data Lazard 2019, biaya modal pembangunan PLTN
adalah yang tertinggi saat ini dimana secara maksimal dapat menyentuh angka
$12.250/kW. Sedangkan energi terbarukan, baik itu angin dan surya telah
mencapai grid parity (harga yang sama dengan pembangkit konvensional pemasok
sistem grid) di banyak negara di dunia//
Paragraf ini merupakan
bukti nyata cherry-picking yang dilakukan oleh Greenpeace. Mereka hanya
mengutip satu angka yang merupakan anomali bahkan dalam industri nuklir
sendiri. Meski memang Greenpeace mengatakan “dapat menyentuh angka,”
ketidakjujuran dalam menyampaikan sisi lain dari rentang tersebut menunjukkan
bahwa mereka bermain kotor.
PLTN Hinkley Point C
(HPC) di Somerset, Inggris Raya, merupakan PLTN termahal di dunia. Nyatanya,
overnight cost HPC ‘hanya’ USD 9.070/kW [20]. Angka ini memang tinggi, tetapi
tidak sampai USD 12.200 sebagaimana disebutkan dalam laporan Lazard [21].
Sementara, PLTN Vogtle yang kemungkinan menjadi basis angka tertinggi di
laporan Lazard, merupakan anomali yang khas hanya terjadi di Amerika Serikat
dan desain AP1000 [22].
Greenpeace sama sekali
mengabaikan bahwa vendor PLTN lain tidak mengalami hal serupa. KEPCO sukses
membangun PLTN Shin Kori unit 3 dan 4 dengan overnight cost USD 2.400/kW [23].
Mengapa bisa rendah? Karena standardisasi desain dan pengalaman pembangunan
[24], sehingga KEPCO dapat mereduksi biaya konstruksi dengan baik.
Lagipula, menggunakan
overnight cost belaka merupakan penyesatan argumen. Greenpeace sama sekali
mengabaikan faktor kapasitas yang menentukan berapa besar harga listrik yang
dihasilkan [25]. PLTN mampu mencapai faktor kapasitas 90%, sementara PLTS dan
PLTB bisa mencapai 20% di Indonesia saja sudah beruntung. Butuh 4-5x kapasitas
terpasang PLTS dan PLTB untuk bisa menyamai luaran listrik dari PLTN.
Greenpeace pun
mengabaikan sama sekali akan berapa banyak listrik yang sebenarnya dapat
dihasilkan selama usia pakainya. PLTN memiliki usia pakai standar selama 60
tahun, bisa diperpanjang hingga 100 tahun. Sementara, PLTS dan PLTB hanya bisa
beroperasi maksimal 30 tahun sebelum harus diganti, itupun kalau tidak rusak
duluan. Sehingga, butuh 2-3x pembangunan PLTS dan PLTB untuk menyamai usia
pakai PLTN.
Total, PLTS dan PLTB
butuh biaya 6-8x dari biaya aslinya untuk bisa menyamai luaran listrik PLTN.
Artinya, PLTS dan PLTB tidak semurah yang diklaim Greenpeace. Khususnya bahwa
angka tersebut mengabaikan sama sekali energy storage dan grid upgrade yang
sangat diperlukan untuk bisa menampung energi bayu dan surya. Artinya, banyak
additional cost yang tidak diungkapkan sama sekali dengan Greenpeace. Apakah
ini merupakan bentuk kebodohan terhadap ilmu fisika dan rekayasa teknik ataukah
memang tujuannya menyesatkan opini publik?
Mengingat mahalnya PLTN
merupakan fenomena unik di dunia Barat dan tidak muncul di Asia, tidak ada
alasan untuk menganggap fenomena tersebut akan terjadi di Indonesia, jika
Indonesia memutuskan untuk go nuclear. Kedatangan PLTN Generasi IV pada dekade
2020-an akan memangkas biaya PLTN lebih rendah dan memastikan halusinasi
Greenpeace tidak akan terwujud.
//Sudah seharusnya
pemerintah Indonesia mulai berpikir jernih dengan fokus berinvestasi pada
energi terbarukan yang lebih aman, murah, bersih, dan bukan PLTU Batubara
apalagi PLTN.//
Jika Indonesia ingin
menjadi negara industri yang maju, salah satu hal yang wajib dipastikan adalah
suplai energi yang murah, melimpah, dan andal. Energi terbarukan tidak bisa
memenuhi satupun dari kriteria ini. Ketika full-cost diterapkan, energi
terbarukan akan menjadi mahal. Tanpa adanya energy storage dan grid upgrade
yang mahal, energi terbarukan tidak bisa menghasilkan listrik yang melimpah dan
andal. Apa hal seperti ini yang mau ditawarkan pada Indonesia?
Hanya nuklir yang dapat
memenuhi kriteria murah, melimpah, dan andal. Ditambah lagi nuklir itu selamat,
bersih, dan berkelanjutan. Untuk memenuhi salah satu syarat sebagai negara
maju, Indonesia mau tidak mau harus memanfaatkan energi nuklir semaksimal
mungkin. Utopia energi terbarukan hanya halusinasi kalangan eco-fascist yang
tidak realistis dalam dunia abad 21.
Referensi:
- Greenpeace Indonesia.
DIakses dari https://www.instagram.com/p/B8u4qmoBgPi/?igshid=16xoq97szaeen
- Undang-Undang No. 10
Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran
- Paparan Radiasi di
Perum Batan Indah Tangsel Turun hingga 90%.
Diakses dari https://megapolitan.okezone.com/read/2020/02/18/338/2170242/paparan-radiasi-di-perum-batan-indah-tangsel-turun-hingga-90
- BATAN Lakukan Clean Up
Daerah Terpapar Radiasi. Diakses dari http://batan.go.id/index.php/id/publikasi-2/pressreleases/6267-batan-lakukan-clean-up-daerah-terpapar-radiasi
- Bapeten: Radiasi Nuklir
di Serpong Tidak Cemari Air Tanah. Diakses dari https://koran.tempo.co/read/metro/450191/bapeten-radiasi-nuklir-di-serpong-tidak-cemari-air-tanah
- R Andika Putra Dwijayanto. Bagaimana Mengelola Limbah Radioaktif PLTN? Diakses dari https://warstek.com/2018/04/10/limbahpltn/
- R Andika Putra
Dwijayanto. Menguak Mitos Bahaya Limbah Radioaktif. Diakses dari https://warstek.com/2018/01/30/mitoslimbah/
- Francois Gauthier-Lafaye.
“2 billion year old natural analogs or nuclear waste disposal: the natural
nuclear fission reactors in Gabon (Africa),” Applied Physics, vol. 3,
pp. 839-849, 2002.
- R. Hagemann and E.
Roth. “Relevance of the Studies of the OKLO Natural Nuclear Reactors to the
Storage of Radioactive Wastes,” Radiochimica Acta, vol. 25, pp. 241-247,
1978.
- C. Yu et al., “Minor actinide incineration and Th-U
breeding in a small FLiNaK Molten Salt Fast Reactor,” Ann. Nucl. Energy,
vol. 99, pp. 335–344, 2017.
- T. Takeda, “Minor actinides transmutation performance
in a fast reactor,” Ann. Nucl. Energy, vol. 95, pp. 48–53, Sep. 2016.
- S. Şahin, Ş. Yalçin, K. Yildiz, H. M. Şahin, A. Acir,
and N. Şahin, “CANDU reactor as minor actinide/thorium burner with uniform power
density in the fuel bundle,” Ann. Nucl. Energy, vol. 35, no. 4, pp.
690–703, 2008.
- B. A. Lindley, F. Franceschini, and G. T. Parks, “The
closed thorium–transuranic fuel cycle in reduced-moderation PWRs and BWRs,” Ann.
Nucl. Energy, vol. 63, pp. 241–254, 2014.
- K. Insulander and V. Fhager, “Comparison of
Thorium-Plutonium fuel and MOX fuel for PWRs,” in Proceedings of Global 2009,
2009, p. 9449.
- H. N. Tran, Y. Kato, P. H. Liem, V. K. Hoang, and S.
M. T. Hoang, “Minor Actinide Transmutation in Supercritical-CO2-Cooled and
Sodium-Cooled Fast Reactors with Low Burnup Reactivity Swings,” Nucl.
Technol., vol. 205, no. 11, pp. 1460–1473, Nov. 2019.
- Jemin Desai and Mark Nelson. Are we headed for
solar waste crisis? Diakses dari http://environmentalprogress.org/big-news/2017/6/21/are-we-headed-for-a-solar-waste-crisis
- Michael Shellenberger. If Solar Panels Are So
Clean, Why Do They Produce So Much Toxic Waste? Diakses dari https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/2018/05/23/if-solar-panels-are-so-clean-why-do-they-produce-so-much-toxic-waste/#5fd65602121c
- Unfurling The Waste Problem Caused By Wind Energy. Diakses dari https://www.npr.org/2019/09/10/759376113/unfurling-the-waste-problem-caused-by-wind-energy
- P. Liu and C. Y. Barlow, “Wind turbine blade waste in
2050,” Waste Management, vol. 62, pp. 229-240, 2017.
- Hinkley Point C cost rises by nearly 15%. Diakses dari
https://world-nuclear-news.org/Articles/Hinkley-Point-C-cost-rises-by-nearly-15
- Lazard’s Levelized Cost of Energy Analysis—version
13.0
- Vogtle Electric Generating Plant. Diakses dari https://en.wikipedia.org/wiki/Vogtle_Electric_Generating_Plant
- R Andika Putra Dwijayanto. Bagaimana Jika Investasi
Energi Terbarukan Dialihkan Ke Energi Nuklir? Diakses dari https://warstek.com/2019/09/07/investasi/
- M. Berthelemy and L. E. Rangel, ”Nuclear reactors’
construction costs: The role of lead-time, standardization and technological
progress,” Energy Policy, vol. 82, pp. 118-130, 2015.
- R Andika Putra Dwijayanto. Meluruskan Salah Kaprah Tentang Membaca Kapasitas Terpasang dalam Membangun Pembangkit Listrik. Diakses dari https://warstek.com/2018/05/19/pembangkitlistrik/